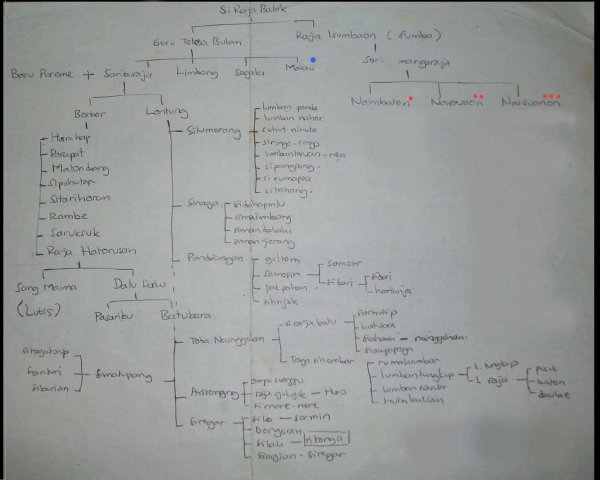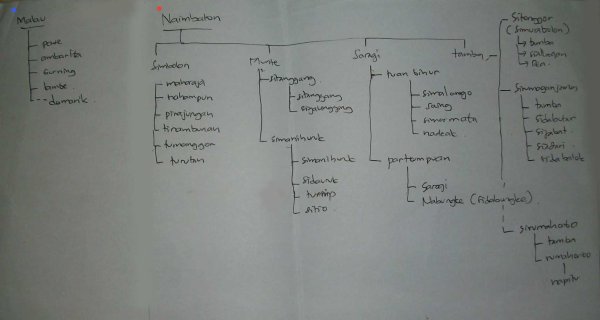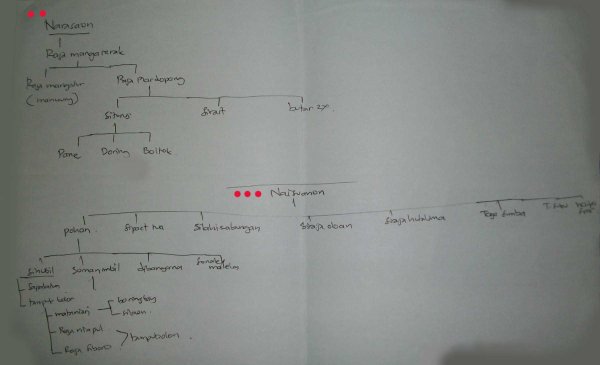Jika ditanya, kenangan apa yang paling membekas saat melaksanakan ibadah puasa dan Lebaran? Saya yakin, sebagian besar kita akan terbawa pada memori masa kecil. Alasannya banyak. Bisa karena masa-masa itu semuanya serba indah dan mudah, atau karena banyak orang-orang yang dulu berpuasa bersama kita, kini sudah tidak ada lagi.
Saya sendiri paling senang kembali ke masa-masa akhir 1970-an sampai 1990-an. Ketika itu, saya masih tinggal di Medan dan kerap menghabiskan hari-hari terakhir berpuasa dan Lebaran di kampung bersama keluarga besar. Biasanya, dua hari menjelang Lebaran kami sudah tiba di kampung.
Kampung kami yang benar-benar kampung itu, terletak di sebuah dusun bernama Aeksah, Kecamatan Pahae Jae, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Jaraknya dari Medan sekitar 325 kilometer atau 8 jam perjalanan darat. Rutenya melewati Perbaungan, Sei Rampah, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Parapat, Balige, Siborong-borong, dan Tarutung.
Tadinya, kedua ompung kami tinggal di Banjar Tikus, Kota Sipirok, yang sekarang jadi Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan. Kota kecil itu berjarak sekitar 22 kilometer dari Aeksah. Setelah pensiun sebagai pegawai sebuah sekolah di sana, ompung pindah ke Aeksah. Saya sempat juga mencicipi puasa dan Lebaran di rumah Sipirok.
Rumah kami di Sipirok berlantai dua dan sebagian berbahan kayu. Dindingnya berdempetan dengan rumah tetangga di kiri dan kanan. Berhubung waktu itu masih terlalu kecil, tidak banyak yang saya ingat. Cuma, satu kebiasaan yang paling membekas adalah saya biasanya tidur di lantai dua, sedangkan kamar mandi ada di lantai satu. Sering di malam hari, kalau kebelet pipis dan malas ke bawah, saya cukup membuka jendela di kamar lantai dua, dan….
Khawatir ada yang melihat? Ya, tidak. Karena pada masa itu penerangan masih seadanya–saya tidak ingat apakah listrik sudah ada atau belum. Yang jelas, untuk menyalakan televisi tabung hitam-putih harus menggunakan catu daya dari aki mobil, yang tiap tiga hari harus dibawa ke pasar untuk dicas.
Begitulah, sekitar saya SD, ompung pindah ke Aeksah, persis di tepi Jalan Raya Lintas Sumatera yang menyambungkan Aceh sampai ke Lampung. Bicara soal listrik, beberapa tahun lamanya kami sempat merasakan kondisi tanpa listrik di Aeksah. Andalan satu-satunya, ya, aki mobil untuk menyalakan radio. Untuk penerangan kami mengandalkan lampu petromaks.
Televisi? Tidak ada satupun gelombang stasiun televisi yang sudi mampir ke Aeksah pada waktu itu. Radio pun biasanya radio luar negeri yang memancar lewat gelombang SW. Sekarang? Jangan ditanya. Semua operator seluler sudah ada memamerkan sinyalnya di sana.
Menjelang berbuka, hari mulai gelap, berjejerlah kami para cucunya yang datang dari Medan, Dumai, dan Sibolga di teras rumah, di hadapan lampu-lampu petromaks yang siap dipompa. Minyak tanah sudah diisi, spiritus sudah dituang, kaos lampu masih oke, siap…mulailah tangan-tangan mungil memompa petromaks sampai suaranya menderu-deru. Kaos lampu berubah menjadi putih terang, pertanda hembusan minyak sudah maksimal.
Beberapa dari lampu-lampu itu kemudian digantungkan di rumah, dua lagi dibawa ke masjid yang berjarak sekitar 400 meter dari rumah. Kecuali khutbahnya yang memakai bahasa Batak yang tak saya pahami, salat tarawih di sana normal. Jumlahnya 11 rakaat. Cuma, karena jaraknya yang cukup jauh dan jalanan gelap, biasanya kami melewatkan tarawih di masjid.
Sayangnya, entah karena apa, saya juga malas mencari tahu, belasan tahun lalu, pengurus masjid pecah kongsi. Terbelah. Dusun yang penduduknya cuma beberapa ratus orang itu pun terpaksa memiliki dua masjid. Pengurus lainnya mendirikan masjid baru di dekat rumah kami.
Enaknya puasa di kampung adalah udaranya yang dingin membuat puasa jadi tidak terasa. Sambil menunggu berbuka kami bermain di kebun dan sawah. Dusun Aeksah dibangun di lereng bukit, termasuk rumah kami. Di depan rumah, dipisahkan oleh jalan, terdapat bukit yang ditumbuhi pohon karet, durian, dan kopi. Sedangkan di lembah di belakang rumah ditumbuhi pohon durian dan kopi.
Permainan yang paling menyenangkan adalah berburu binatang di kebun dan sawah di belakang rumah. Berbekal senapan angin yang disiapkan untuk memburu tupai perusak tanaman, kami serasa jadi pemburu profesional. Mencoba menembak burung, tupai, atau burung ayam-ayam yang sering hinggap di tali air sawah. Untunglah, ketika itu tidak ada satu pun hewan yang berhasil ditembak jatuh oleh para pemburu amatir ini.
ARSIK
Di sebelah sawah di belakang rumah, terdapat kolam ikan mas. Ukurannya kira-kira 10×15 meter. Beberapa bulan menjelang Lebaran ompung selalu menebar bibit ikan mas di sana. Jadi, tiba waktunya Lebaran, ikan-ikan sudah besar dan siap disantap. Nah, salah satu kegiatan yang paling ditunggu-tunggu adalah menangkap ikan mas di kolam.
Menangkap ikan mas di kolam gampang-gampang susah. Pertama, tambak harus dikeringkan dulu. Airnya dibuang lewat saluran pembuangan ke tali air. Setelah surut menjadi kira-kira setinggi 30 sentimeter, barulah kami masuk ke dalam kolam yang penuh lumpur itu.
Lantaran tangguk cuma ada dua, sebagian besar kami memilih menangkap ikan memakai tangan kosong. Lebih merepotkan karena ikannya licin dan sudah besar-besar. Meski begitu, dengan tangan kosong acara menangkap ikan menjadi lebih menyenangkan.
Bayangkan susahnya menangkap ikan di atas lumpur. Jalan saja setengah mati, apalagi harus mengejar si ikan yang lari ke sana-ke mari. Setelah satu jam, barulah semua ikan bisa ditangkap. Jumlahnya mencapai puluhan ekor. Selanjutnya, ikan yang telah dicuci di sungai dibawa ke rumah untuk diolah menjadi arsik.
Arsik ini adalah salah satu hidangan khas Tapanuli yang sangat populer. Cara membuatnya, ikan mas yang sudah disiangi, ditiris, dicuci bersih, dan dibiarkan utuh. Kemudian, badan bagian luar ikan dilumuri dengan bumbu yang sudah disiapkan.
Bumbu-bumbu itu adalah cabai merah, bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, andaliman (merica Batak), kunyit, dan garam. Setelah itu, masukkan kacang panjang dan 3-5 batang serai ke dalam perut ikan. Alas dasar wajan dengan sisa serai sampai tertutup rapat. Letakkan ikan di atas serai, lalu tuangkan air. Tutup wajan dan masak di atas api kecil sampai kering. Dan, voila…this is it, sajian ikan mas dengan topping berwarna kuning meriah yang menggugah selera.
MANGALOMANG
Bersamaan dengan mengolah arsik, sehari menjelang Lebaran ompung dan geng inang boru juga mulai mangalomang atau memasak lemang. Bahan-bahan lemang sederhana, yaitu campuran antara beras ketan, santan, dan garam. Bahan-bahan yang sudah disiapkan dituang ke dalam satu ruas bambu. Di dalam bambu dilapisi terlebih dulu dengan daun pisang supaya lemang tidak lengket.
Bambu kemudian ditegakkan berjejer di atas kayu dan dibakar pakai arang atau kayu bakar. Membakar lemang ini cukup lama waktunya. Bisa setengah harian. Lemang juga harus dibolak-balik supaya matangnya merata. Setelah matang, batang bambu dibelah dan dikeluarkan lemangnya.
Lemang biasanya digunakan sebagai sajian untuk hidangan makan pagi sebelum salat Ied. Lemang paling mantap disajikan bersama durian. Pas, karena lemang bisa menetralisasi rasa manis durian. Kelebihan lainnya, dengan memakan lemang bersama durian, jumlah durian yang kita santap menjadi lebih sedikit.
MADABU TARUTUNG
Durian di kampung tidak perlu beli. Tinggal menunggu ‘durian runtuh’ dalam arti sebenarnya. Sudah saya ceritakan tadi, belasan pohon durian tinggi besar tersedia di kebun di depan rumah dan di lembah di belakang rumah. Menunggu durian runtuh ini juga kegiatan wajib menunggu berbuka.
Apalagi di era kegelapan ketika PLN belum melirik Aeksah, menunggu durian jatuh adalah kegiatan mengasyikkan. Tak peduli siang atau tengah malam, jika terdengar suara gedebuk–pertanda ada buah durian yang mendarat di tanah, orang yang pertama mendengarnya harus meneriakkan, “Madabu tarutung, madabu tarutung,” (jatuh durian, jatuh durian). Secepat Ben Johnson (sprinter zaman dulu) kami pun berlarian ke arah suara itu. Berbekal senter seadanya, pencarian terkadang butuh waktu lama. Tapi begitu ketemu, rasanya senang luar biasa.
Saat musim durian, kadang jumlah durian yang terkumpul melebihi kemampuan makan belasan anak-cucu yang hadir. Dari pada busuk, durian itu kami jajakan di tepi jalan. Tempatnya seadanya. Papan-papan kayu dipaku menjadi meja darurat. Durian diletakkan saja di pinggir tepi jalan. Tidak berapa lama pasti ada saja pemudik yang mampir. Kalau tidak salah ingat harganya ketika itu Rp 5 ribu-Rp 10 ribu per buah. Lumayan, kalau bisa terjual 10 buah, berarti Rp 100 ribu di tangan.
MAKKOBAR
Hari terakhir berpuasa pun tiba. Malam harinya, seperti biasa, warga kampung ikut meramaikan malam dengan takbiran. Tidak hanya dari Aeksah, takbiran dimeriahkan pula oleh warga-warga dari kampung lain di Pahae. Jangan dibayangkan jarak antar kampung menempel rapat seperti di kota besar. Jarak antar kampung di Pahae paling sedikit 3 kilometer.
Selepas berbuka, mulailah muncul keramaian. Warga kampung menyewa beberapa truk yang penuh diisi anak-anak kecil. Di atas kap truk diletakkan speaker besar yang dicomot dari masjid. Sambil berkeliling, gema takbir berkumandang dari atas truk. Kami pun tak mau ketinggalan. Ikut mengiringi dengan mobil dari belakang.
Besoknya, sesuai tradisi masyarakat Batak, sebelum menuju ke lapangan untuk salat Ied, kami sekeluarga berkumpul di ruang tengah rumah. Kursi-kursi digeser, tikar dan karpet dibentangkan. Sebelum menyantap hidangan, ada acara wajib yang dinamakan makkobar.
Dalam sesi ini, seluruh anggota keluarga harus menyampaikan sepatah-dua patah kata yang intinya ucapan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh keluarga. Makkobar selalu dimulai dari cucu yang paling bontot, kemudian ke anak yang paling bontot, terus bergiliran sampai akhirnya sampai ke ompung godang (kakek laki-laki).
Teorinya hanya sepatah-dua patah kata, tapi prakteknya, makin tua umur pembicara, makin panjang pula petuah yang disampaikan. Banyak orang yang bilang, tradisi makkobar ini yang membuat orang Batak jago berbicara di depan umum dan adu argumentasi. Terbukti, jagad hukum sekarang dikuasai orang Batak.
Tapi, terus terang, makkobar ini yang selalu bikin saya senewen tiap tahun. Gimana gak, malamnya harus membuat konsep apa yang mesti disampaikan besok. Harus ada kalimat yang baru, dong. Doanya juga mesti tambah variatif, masa’ sama dengan tahun lalu. Ya, begitulah saban tahun.
Habis makkobar dan sarapan, sekitar pukul 7.00 kami pun beramai-ramai berangkat ke tanah lapang yang berjarak 500 meter dari rumah. Tanah lapang itu sebenarnya halaman rumah warga yang sangat luas, jadi bisa dipakai untuk salat seisi kampung.
Salat di Tapanuli Utara sama dengan salat umat Islam di seluruh dunia. Dimulai dengan takbir, kemudian khutbah Ied, dan ditutup dengan salat dua rakaat. Yang membedakan paling khutbahnya yang menggunakan bahasa Batak yang hanya 10 persen yang bisa saya cerna.
Selesai salat, kami kembali ke rumah. Sampai tengah hari biasanya, kami tidak bisa kemana-mana. Sebagai orang yang cukup dituakan di kampung itu, ompung ramai menerima tamu. Anak-anaknya pun harus siaga di rumah. Selain untuk bersilaturahim, tugas paling penting menyiapkan amplop untuk dibagikan kepada anak-anak kecil yang datang.
ABIT
Begitu tamu mulai berkurang–sebenarnya tidak pernah sepi sampai malam, anak dan cucu biasanya pergi ke Sipirok untuk jalan-jalan. Sepanjang perjalanan 20 kilometer lebih menuju Sipirok yang masuk ke Kabupaten Tapanuli Selatan itu, akan terlihat parade baju baru anak-anak maupun orang tuanya. Biasanya warna-warna yang dipilih adalah cerah yang ngejreng.
Uniknya di sana, meski sudah memakai baju baru, tetap saja sehelai sarung atau abit terlempang di pundak atau di pinggang mereka. Jadinya kontras dengan baju serba baru dari kepala ke kaki yang mereka kenakan. Lah, keren-keren kok pakai sarung. Namun, itulah tradisi masyarakat Tapanuli. Mungkin karena sehari-hari terbiasa mengenakan sarung untuk menghalau dingin, saat Lebaran pun sarung harus ikut.
Masyarakat Batak, sebagaimana banyak suku lain di Nusantara, memang sangat lekat dengan kain-kain yang dibuat dengan teknik menenun (proses membuat kain dengan cara menyilangkan dua set benang secara vertikal-horisontal). Kain tradisional masyarakat Batak dikenal dengan nama ulos.
Ulos dibuat bukan dengan teknik tenun biasa, melainkan dengan teknik tenun ikat. Disebut tenun ikat karena pada saat benang hendak diwarnai, benang dikumpulkan, diikat satu per satu, baru dicelupkan ke cairan pewarna. Metode ini yang menghasilkan corak-corak tertentu dari kain.
Ulos banyak jenisnya, tergantung tujuan penggunaannya. Misalkan, ulos untuk dipakai sehari-hari (ulos Sirampat) berbeda ulos dengan ulos untuk upacara adat (ulos Ragidup atau ulos Ragihotang) , beda pula dengan ulos untuk berkabung (ulos Sibolang). Ah, soal ulos dibahas nanti ya, sekarang perjalanan kita lanjutkan ke Sipirok dulu…
AEK LATONG
Jarak perjalanan ke Sipirok tidak terlalu jauh, hanya sekitar 20 kilometer. Lalu-lintas juga sepi dan lancar. Tapi, jangan dikira perjalanan bisa ditempuh dengan cepat. Salah satu hambatan ada di sebuah daerah yang bernama Aek Latong. Di sini ada jalan ‘maut’ sepanjang 3-4 kilometer yang dari tahun ke tahun selalu anjlok sedalam puluhan meter.
Sudah banyak korban jiwa yang menjadi tumbal di kawasan ini. Pilihan kecelakaan ada dua. Pertama, mobil bisa terlempar ke jurang karena terlambat mengurangi kecepatan sewaktu memasuki jalan yang tiba-tiba menurun tajam. Kedua, mobil terseret ke bawah karena tidak kuat menaiki tanjakan curam.
Selain jebakan jalan turun, tantangan di jalan mendaki juga berat. Terutama di musim hujan. Bus-bus besar dan sedang biasanya menurunkan semua penumpangnya sebelum mendaki di jalan ini. Beberapa bus yang nekad tak menurunkan penumpang atau mengurangi muatan harus menerima nasib melorot ke bawah atau terguling. Konon kabarnya, ada satu bus yang terguling dan masuk ke dalam rawa berair yang di sisi jalan. Semua penumpangnya tewas tenggelam.
Untungnya, saya dengar kabar, jalur Aek Latong kini sudah digeser oleh Kementerian PU sekitar satu kilometer dari jalan aslinya. Jalan baru sepanjang 2,9 kilometer yang dibangun dengan biaya Rp 60 miliar sudah beroperasi tahun ini. PU mengakui, penanganan jalur Aek Latong sangat berat.
Pasalnya, kondisi alam Aek Latong tepat berada pada patahan bumi Sesar Semangko, sehingga selalu terjadi patahan yang sangat besar di badan jalan. Kondisi inilah yang menyebabkan rusaknya badan jalan. Masalah lainnya, jalur tersebut berada pada daerah lereng gunung yang curam. Ditambah curah hujan yang tinggi, lengkap sudah kerawanan di jalur Aek Latong.
Dari berbagai literatur diketahui bahwa sesar atau patahan Semangko adalah istilah yang merujuk pada bentukan geologi yang membentang di Pulau Sumatera dari utara ke selatan, dimulai dari Aceh hingga ke Teluk Semangka di Lampung.
Patahan inilah membentuk Bukit Barisan, rangkaian dataran tinggi di sisi barat Sumatera. Patahan Semangko berusia relatif muda dan paling mudah terlihat di daerah Ngarai Sianok dan Lembah Anai di dekat Bukittinggi.
Sesar Semangko ini, kata pakar kegempaan Danny Hilman, sebenarnya masih bagian dari sesar Sumatera yang terjadi akibat tunjaman yang miring dari lempeng Indo-Australia terhadap Eurasia.
Danny membagi patahan Sumatera sepanjang 1.900 kilometer menjadi 19 segmen besar. Mulai dari segmen Sunda di ujung selatan, Semangko, Kumering, Manna, Ketaun, Dikit, Siulak, dan Suliti. Kemudian Sumani, Sianok, Sumpur, Barumun, Angkola, Toru, Renun, Tripa, Aceh, dan Seulimeum. Tiap segmen panjangnya beragam, mulai dari 35 sampai 220 kilometer.
Gempa darat yang disebabkan patahan itu sangat dangkal, hanya pada kedalaman 10 kilometer, sehingga memicu efek getaran sangat besar dan dapat menggoncang lapisan bumi dengan kuat walaupun magnitude-nya kecil. Wilayah yang dilalui patahan Semangko ini sangat rentan terhadap longsor.
Tuh, beralasan kan, mengapa Aek Latong sulit sekali ditangani.
SIPIROK
Tiba di Sipirok banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Pertama-tama, kita harus melewati hiruk-pikuk pasar yang ada di tengah kota. Saya ingat, waktu kecil, ompung masih sering berdagang di pasar ini. Sebelum terbakar habis dan dibangun kembali menjadi lebih modern, dagang di pasar ini masih lesehan. Ompung menggelar tikar dan berdagang hasil bumi dari Aeksah.
Ada telur ayam, sayur-mayur dan buah-buahan. Kerja saya yang niatnya ingin membantu biasanya cuma ngerecokin atau mecahin telur. Satu lagi, bakat terpendam dari kecil sampai sekarang adalah nyasar. Beberapa kali saya nyasar di pasar yang cukup besar itu. Apalagi dulu kondisi belum serapih sekarang.
Tujuan utama di Sipirok ada dua yakni pemandian aek milas (air panas) Sosopan dan Tor Simago-mago (tor artinya gunung, mago artinya hilang). Aek milas sosopan terletak di pertengahan jalan menuju simago-mago. Dari Sipirok ke Sosopan jaraknya sekitar 5 kilometer. Ditambah sekitar 3 kilometer lagi menuju Simago-mago.
Aek Milas Sosopan ini adalah pemandian umum air panas yang gratis. Gak kalah dengan onsen di Jepang, lah. Letaknya persis di tepi jalan. Bedanya dengan onsen, di sini gak boleh mandi tanpa busana. Bedanya lagi, di Sosopan tidak ada orang yang bisa berendam, saking panasnya air di sana. Pengunjung hanya duduk di tepi kolam lalu mandi dengan air yang sudah didinginkan di dalam gayung.
Tahun lalu saya ke sana, rasanya kok ada penurunan. Sangat jorok. Sampah sampo dan sabun di sana-sini. Dulu lebih bersih. Entahlah. Selain di Sosopan, pemandian air panasnya lainnya ada di Padang Bujur. Tempatnya agak jauh ke dalam. Mungkin karena itu tempatnya menjadi kurang popular meski kabarnya lebih bersih. Saya pernah ke sana, tapi tidak pernah mandi, hanya nongkrong di warung.
Adanya sumber mata air panas di satu wilayah biasanya menunjukkan ada aktivitas gunung api di sana. Di Sipirok juga begitu. Kota ini bertetangga dengan Gunung Sibualbuali (1.819 meter di atas permukaan laut), yang termasuk gunung api aktif kategori B. Artinya, meski aktif, gunung ini tidak pernah menunjukkan aktivitasnya sejak tahun 1.600-an. Kata para ahli geologi, gunung ini terbentuk akibat amblasan (graben) sesar Sumatera yang berarah baratlaut-tenggara, sedikitnya terbentuk tiga kawah besar pada bagian puncak dan lerengnya.
Sedangkan Gunung Si Mago-mago yang jadi obyek wisata populer warga setempat hanyalah bukit kecil yang sama sekali tidak aktif. Bagi yang memakai kendaraan, bisa membawa kendaraannya naik ke atas puncak, karena sudah disediakan jalan beraspal yang landai. Mau jalan pun tidak sulit. Paling sekitar 15 menit sudah tiba di puncak. Dekat, kan.
Konon, dinamakan Si Mago-mago karena orang yang datang ke Si Mago-mago akan kelihatan hilang-timbul jika sudah di atas puncaknya. Benar-tidaknya saya tidak yakin. Karena selama ke sana tidak pernah ada yang hilang, tuh. Pemandangan dari atas gunung cukup menyenangkan mata. Angin dingin yang menyapu badan juga nyaman untuk menjadikan gunung ini sebagai tempat kongkow yang murah-meriah.
Oiya, datang Sipirok kurang paripurna kalau tidak mampir ke rumah makan sop Sipirok di dekat pasar. Sop iga sapi di sini terkenal enak, sepadan dengan harganya. Pemiliknya juga sudah membuka cabang di Medan. Satu lagi penganan favorit saya adalah keripik sambal Taruma. Ini adalah keripik singkong yang di dalamnya dikasih sambal ulek merah. Keripiknya sih biasa, sambalnya itu yang bikin ketagihan.
**